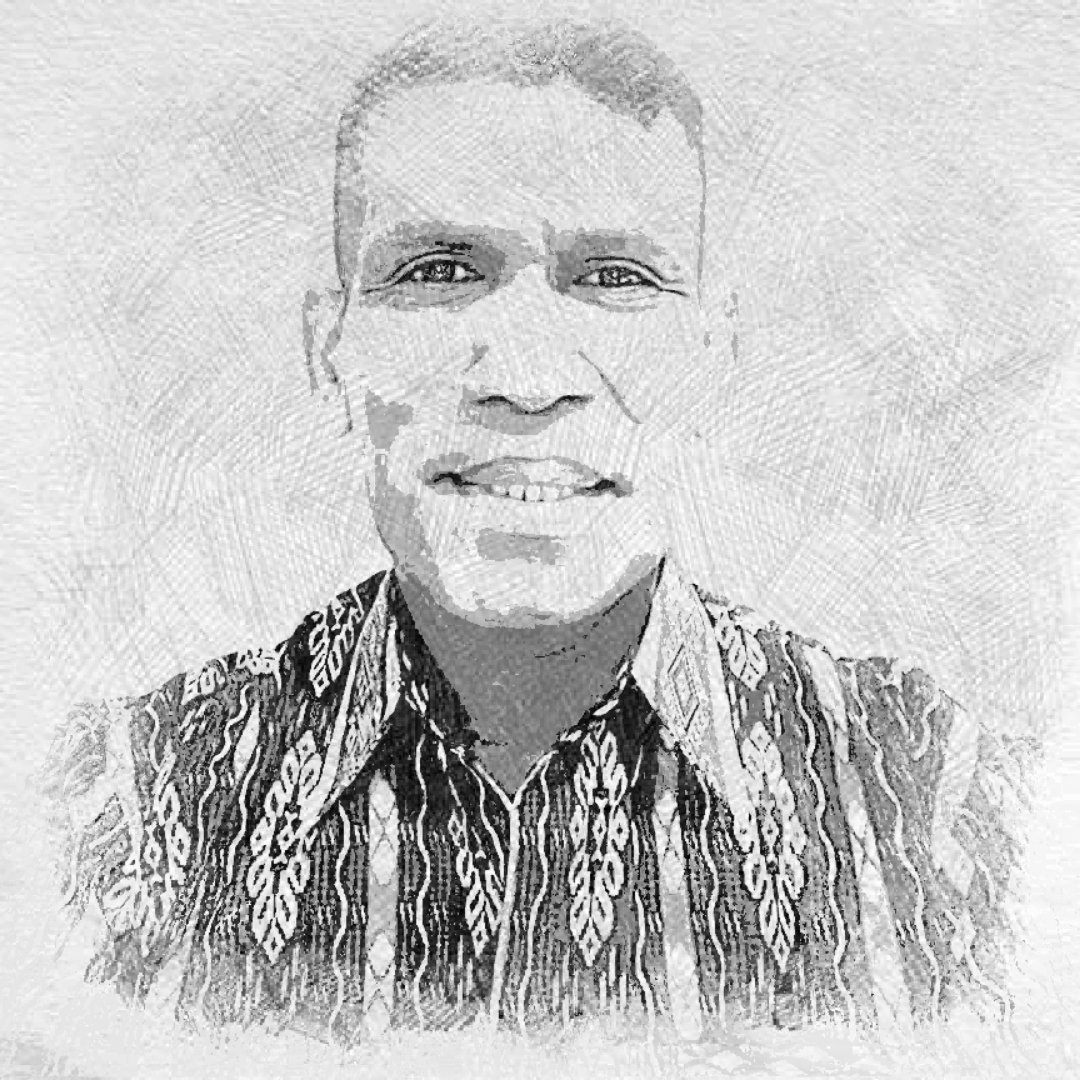
Oleh: Petrus Polyando (18/06/2022)
Diskursus tentang sirkulasi elit dan kepemimpinan nasional semakin hari semakin sexy disorot seiring berakhirnya rezim kekuasaan atau menjelang masa waktu suksesi kepemimpinan nasional. Berbagai kalangan seperti praktisi politik, elit, ilmuwan, kelompok gerakan sosial, mahasiswa dan juga sebagian kelompok ekonom lainnya mulai mewacanakan tentang sosok ideal yang menjadi pemimpin negara pada siklus berikutnya. Masing-masing pihak mulai mengambil sikap untuk menentukan figur yang hendak diperjuangkan pada sesi pemilihan berikutnya. Ada yang terang-terangan membicarakan nama ada yang belum menentukan nama bahkan baru sebatas menentukan kriteria. Ada yang terlihat cukup rasional membicarakannya dari aspek kebutuhan negara saat ini terhadap pemimpin dengan terlebih dahulu memetakan masalah dan kriteria yang diinginkan, sementara itu ada juga yang sangat emosional berdasarkan kedekatan tertentu menunjuk orang yang menurutnya harga mati untuk menjadi pemimpin berikutnya. Semuanya tentu lumrah, absah atas dasar kepentingan para pihak, yang tersimpan di alam pikiran mereka.
Namun demikian, sorotan kritisnya adalah apakah pemimpin yang dibicarakan itu adalah juga sosok negarawan Kalokagathos? Istilah Kalokagathos ini sebenarnya merujuk pada ajaran era homeris dan Sofisme abad ke-5 sebelum masehi yang menggambarkan sosok manusia utama yang ciri-cirinya bersifat estetis kalos (indah-elok) dan etis agathos (baik), manusia yang memiliki nilai bagi dirinya sendiri selalu menjadi yang terbaik dan lebih unggul dari orang lain (Wibowo & Cahyadi, 2014). Kalokagathos ini merupakan konsep yang lebih maju dari sekedar elitis atas dasar keturunan aristokrat dan oligarki atas dasar kekayaan serta atribut simbol jabatan lainnya. Maknanya lebih maju yakni manusia yang paripurna berkat pendidikan dan derajat kebudayaannya. Tentu jawabannya beragam dengan melihat realitas figur yang diwacanakan, ada yang ragu, ada yang dengan tegas meyakinkan jagoannya adalah sosok paripurna dimaksud. Yang ragu tentu memiliki basis pertimbangan rekam jejak yang diketahuinya, sementara yang yakin memiliki argumentasinya dari sisi yang berbeda.
Saat ini banyak figur yang dimunculkan ditengah masyarakat, yang menimbulkan sikap saling mengklaim bahkan saling mendegradasi satu sama lainnya. Pro dan kontra sebenarnya bukanlah hal tabuh bagi kehadiran seorang pemimpin Kalokagathos apalagi di alam demokrasi, namun menjadi soal bila yang dipolemikan tidak memiliki nilai unggul yang memilki keutamaan sebagai manusia paripurna. Faktanya banyak sosok yang dihadirkan tetapi masih sebatas elitis aristokratis dan oligarkhi yang secara umum publik dapat dengan mudah menghubungkannya. Dan persepsi publik ini tidak terbantahkan berdasarkan jejak relasi yang terjadi. Padahal sosok Kalokagathos itu meskipun dia dibenci, ditentang oleh masyarakat karena perilakunya yang berbeda (unik) dari kebiasaan / budaya masyarakat, namun dia tetap memelihara fokus untuk mengubah pakem sosial yang menyiksa dalam alam tradisi tersebut. Dia bekerja mandiri bukan menggantungkan pada keterberian atau fasilitas yang ada, namun keluar dari kebiasaan dan lingkungan nyaman, menggapai tujuannya dan kembali memperbaharui kondisi komunitasnya agar keluar dari goa kegelapan.
Pertanyaan selanjutnya darimanakah pemimpin dan negarawan Kalokagathos itu? Atau kalau dikonkritkan di ruang mana saja kita bisa peroleh mereka? Bagaimana kita bisa mengetahui seseorang itu adalah sosok pemimpin dan negarawan dimaksud? Apakah bisa dibentuk? Sejatinya dari alegori sosok pemimpin kalokagtahos di atas tersirat jawaban bahwa mereka yang unggul yang diterima sebagai pemimpin ideal ini memiliki kegigihan perjuangan yang tidak kenal lelah, mengasah dirinya, membangun jati dirinya dan berhasil membuktikan pencapaian tujuannya secara outodidak. Artinya dia tidak melalui proses pendidikan tertentu tetapi atas panggilan nuraninya untuk mengubah diri dan lingkungannya. Dia berusaha melihat secara berbeda dari pandangan umum yang telah mengekang orang dari waktu ke waktu. Dalam perkembangannya manusia semakin sadar bahwa jumlahnya terus bertambah (sebagaimana juga ditegaskan Thomas Robert Maltus (1798) dalam tesisnya bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur), yang tentu akan menjadi masalah kalau tidak ada pemimpin yang mengelola, mengendalikan dan mengubahnya untuk kebaikan hidup bersama secara teratur dan berkelanjutan. Bila mengharapkan pemimpin ideal yang terlahir dari alam (proses autodidak), maka dunia akan semakin sulit dikendalikan dan pasti terjadi kekacaubalauan. Hal ini mengingat pemimpin seperti ini kemunculannya sulit diprediksi dalam siklus yang teratur atau periode waktu yang ditentukan. Bisa satu dekade, bisa satu abad, bisa satu generasi tanpa ada yang mengetahuinya secara pasti. Atas kondisi ini, muncul gagasan perlu dibentuk pemimpin ideal dimaksud.
Alasan dibentuk pemimpin ideal meski bukanlah berdasar ilustrasi dangkal di atas, tetapi oleh para sofis (Abad ke- 5 SM) dengan kisah dan latar peristiwa di Athena pada masa itu, telah membuka diri bahwa pemimpin ideal yang elok dan baik perlu dibentuk untuk menjawab krisis pemimpin. Kesadaran kolektif mereka ini kemudian menimbulkan perdebatan mengenai sosok pemimpin ideal antara para Sofisme dengan Sokrates dan Platon (abad ke-5-4 SM). Dialektika intelektual mereka soal proses menghadirkan pemimpin ideal yang baik dari sudut pandang yang berlawanan. Pada saat itu kaum Sofisme mengajarkan bahwa pemimpin yang baik itu harus bisa berorasi atau seorang orator yang ulung sehingga yang ditekankan adalah pembentukan ketrampilan bernalar lewat penguasan bahasa (grammar), cara berwacana (rethoric), serta cara berpikir yang jernih dalam menarik sebuah kesimpulan (dialectic). Ajaran Sofis hanya fokus pada kemampuan olah pikir agar memiliki ketangkasan berargumentasi dan berkata-kata. Hal ini dikritik oleh Platon bahwa pemimpin ideal harus melalui pendidikan (paideia) lewat pancaindera, mulai dari tahap sensibilitasnya lewat seni dan gimnastik sampai pada puncaknya dialektika dalam memahami ilmu abstrak. Platon secara tegas merumuskan tahapan membentuk seorang pemimpin dengan memadukan sisi kejiwaaan dan kejasmanian mulai dari menata jiwa melalui musik, kemudian pendidikan jasmani untuk menggembleng daya tahan tubuh dan mental agar jujur, disiplin dan berani melalui pendidikan militer. Tahap ini selesai kemudian diseleksi untuk mengikuti tahap lanjutan yaitu membentuk karakter intelektual yang akan dipromosikan menjadi pemimpin dan memasuki masa penugasan (Plato, 1970; Wibowo, 2011). Tampaknya Platon lebih komprehensif merumuskan pembentukan pemimpin Kalokagathos melalui mekanisme pendidikan. Bahkan secara rinci mengidentifikasi tahapan waktu dan materi ajar yang perlu dilatih kepada calon pemimpin tersebut.
Bila menganalisis lebih jauh, timbul pertanyaan kritis darimana gagasan Platon ini, sehingga penuh keyakinan bahwa dengan proses pendidikan (paideia) yang diusulkannya akan melahirkan pemimpin ideal. Jawabannya tentu Platon melihat kondisi faktual masa itu dan juga berusaha mematahkan gagasan para Sofis. Lebih dari itu sebenarnya Platon melihat dengan cara yang berbeda dalam alam pikirannya yang dikenal dengan dunia ideanya, melahirkan gagasan pemimpin yang memiliki jiwa yang lepas dari keterberiannya, sebagaimana yang dituangkan dalam alegori goanya. Hal ini kemudian menjadi permenungan diri, memaknai, mengkategorisasi profil pemimpin yang ideal yang dapat dibentuk dengan meniru perilaku pemimpin yang ada dalam pikirannya. Dari sinilah dapat dipahami bahwa pemimpin ideal yang elok dan baik (Kalokagathos) itu, berasal dari dua sumber yaitu terlahir secara alami (proses autodidak) dan dibentuk melalui pendidikan (paideia).
Gagasan pendidikan pemimpin Kalokagathos Platon ini, kemudian menjadi insipirasi pengembangannya berbagai negara di belahan dunia dari waktu ke waktu. Di Indonesia, salah satu konsep pendidikan (paideia) yang secara historikal dan filosofis memiliki keutamaan yang persis seperti model Platon adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Dari sejarah yang tertulis maupun cerita turun-temurun yang diwariskan para pendiri maupun para pendahulu yang dibentuk dari lembaga ini, umumnya sepakat bahwa sejak awal berdirinya lembaga ini telah meletakan keutamaannya pada upaya melahirkan pemimpin dan negarawan. Ini bisa di lihat dari konsistensi peserta didik yang selektif, kurikulum yang terfokus, pola pendidikan dan juga orientasi output yang dihasilkan. Meski ada sedikit pergeseran perilaku dari yang disebutkan namun secara hakikat sebenarnya masih utuh dan sama dari awal sampai saat ini yaitu keutamaan pendidikan yang dibentuk adalah kader pemimpin Kalokagathos.
Alegori pendidikan pemimpin dan negarawan di Lembah Manglayang ini dimulai dengan proses seleksi peserta didik meski sebenarnya ada sedikit cerita seleksi yang secara materi belum sejalan dengan hakikat dasar Platon. Namun tentu ini bisa diterima dengan alasan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan bangsa ini. Karena memang Platon menyarankan calon peserta didik yang hendak dilatih menjadi pemimpin itu syarat utamanya seleksi mengenai bakat bawaan pemimpin. Mereka telah memiliki potensi yang berbeda dan unggul dari yang lainnya. Selanjutnya dalam proses pendidikan, sebenarnya lembaga ini mengembangkan pada tahap kedua dari gagasan Platon yaitu menata jiwa melalui musik dan penggemblengan mental melalui disiplin dan latihan militer. Ini pun meski ada sedikit bias mengenai proses yang dianggap tidak sempurna atau kurang total sehingga hasilnya kurang optimal terutama soal waktu yang lebih singkat dari gagasan Platon. Platon menggagas pembentukan mental jiwa dengan musik selama 6 (enam) tahun kemudian diikuti dengan pelatihan miilter 2 (dua) tahun, setelah itu peserta didik diseleksi untuk tahap lanjutan. Bagi yang gagal dapat kembali bertugas sebagai tentara atau kembali ke masyarakat sesuai dengan panggilannya. Sementara IPDN menggabungkannya dalam waktu pendidikan hanya 4 (empat) tahun. Pembentukan mental melalui disiplin dan militer hanya ditempuh dalam waktu 2 (dua) minggu sampai 1 (satu) bulan dengan materi dasar yang terbatas, sedangkan pendidikan mental jiwa selain melalui musik namun juga dalam bentuk kerohanian. Dari sisi pembentukan karakter intelektual, IPDN sebenarnya menggabungkan dari awal masuk pendidikan sampai pada akhir pendidikan selama 4 (empat) tahun. Mulai tingkat satu sampai pada tingkat empat peserta didik telah diajar atau diantarkan memahami ilmu-ilmu abstraksi dengan kadar yang bervariasi. Dalam gagasan Platon justru proses ini dilakukan setelah pendidikan militer dan disiplin, serta hanya terbatas mereka yang telah lulus seleksi. Hal yang mungkin persis sejalan dengan ide besar Platon adalah tahap penugasan kemudian diseleksi mengikuti pendidikan lanjutan yang nantinya siap untuk menjadi pemimpin dengan berbagai bekal yang telah diajarkan.
Sejenak direnung, negara ini sebenarnya telah melahirkan maha karya yang fundamental yang mempersiapkan lembaga pendidikan (paideia) untuk para pemimpin dan negarawan yang elok dan baik. Secara filosofis ada benang merah antara tahapan proses yang ada di lembaga ini dengan gagasan besar Platon. Proses pendidikan yang berlangsung puluhan tahun sebenarnya telah menghasilkan ribuan kader pemimpin yang elok dan baik (Kalokagathos), sebagaimana yang diimpikan Platon. Meskipun harus diakui ada sebagian kecil yang bermasalah namun umumnya alumni lembaga ini telah memberikan kontribusi bagi kebaikan bangsa dan negara di berbagai level pusat maupun daerah. Bahkan publik masih percaya bahwa lembaga ini menjadi sumber lahirnya pemimpin dan negarawan yang memiliki keunggulan paripurna sebagai manusia sehingga kelak mampu menghadirkan kebaikan bersama. Secara riil, harus diterima penyelenggaraan pendidikan saat ini mengalami pergeseran praktik di luar kerangka besar hakikat pendidikan kader pemimpin dan negarawan Kalokagathos. Ini bisa diidentifikasi seperti halnya orientasi pendidikan dari calon pemimpin dan negarawan menjadi sebatas calon birokrat. Kemudian seleksi peserta didik yang belum mengutamakan pada bakat pemimpin. Penyelenggaraan pendidikan pada beberapa lokasi, atau tidak terpusat pada satu area. Meskipun telah mengakomodasi perubahan sosial dan faktor eksternal lainnya namun ada yang belum sejalan dengan kerangka filosofis dihadirkan lembaga ini.
Tampak ada gap yang besar sehingga disarankan perlu restorasi dan pembaharuan. Perlu mengembalikan orientasi dan semangat keutamaan pendidikan pada lembaga pendidikan calon pemimpin dan negarawan bukan sebatas birokrat. Melakukan seleksi terbatas berfokus pada pencarian bakat pemimpin yang siap dibentuk di IPDN. Pemusatan pendidikan pada satu lokasi yang terkonsentrasi secara total. Konsisten dengan kurikulum dan sistem pendidikan yang mengakomodasi upaya menata jiwa, menggembleng mental dan pembentukan karakter intelektual secara kontinu. Kemudian mengawal mereka secara menyeluruh saat penugasan sampai waktunya diseleksi mengikuti pendidikan lanjutan dan kelak mereka siap menjadi pemimpin yang diharapkan.
Dengan demikian akan tercipta pendidikan yang benar-benar fokus mendidik calon pemimpin dan negarawan di IPDN dengan prinsip keutamaan sebagai manusia paripurna yang unggul dari yang lainnya. Dalam hal ini, melahirkan kader yang tidak berorientasi pada kepentingan partikular, tidak rakus kekuasaan namun diharapkan banyak orang untuk memimpin karena keunggulannya, tidak mudah goyah dan dipengaruhi oleh kelompok haus kekuasaan, selalu menciptakan kebaikan bersama, dan menjadi solusi atas kekacaubalauan yang terjadi. Melalui pendidikan di IPDN dapat membalikan penglihatan mereka (conversio) kesegala arah, mengeluarkan mereka dari goa kegelapan sehingga mampu melihat terang cahaya yang pada akhirnya mereka sadar dan kembali untuk membantu mengeluarkan orang-orang yang terkurung dalam goa tersebut. Singkatnya, mereka yang dibentuk dan kelak memimpin adalah mereka yang memiliki kebaikan jiwa secara paripurna, berusaha maksimal melampaui yang lainnya, keluar dari kebiasaan yang membelenggu, tidak putus asa dan mudah pasrah. Selanjutnya berlaku jujur untuk mempengaruhi orang lain, dan juga tegas bahkan mampu menghukum diri sendiri, keluarga dan para sahabat bila berbuat tidak adil-tegak-benar dan mampu berorasi atau berbicara dengan baik dan konsisten dengan perilakunya bertindak adil, tegak dan benar (Georgias 508a, dalam Wibowo & Cahyadi, 2013).
Hal yang telah baik selama ini terus dipertahankan, namun hal yang bergeser dari hakikat dasar perlu dikembalikan agar keutamaan lembaga ini, sebagai pengawal negara, dapat terwujud. Negara hadir sebagai kesepakatan guna menjadi solusi atas sisi manusia sebagai komunitas duniawi yang dipersepsikan sebagai komunitas yang buruk, tamak, rakus dan berorientasi pada kepentingan duniawi semata sebagaimana digambarkan olef filsuf Augustinus (354-430M), membutuhkan pemimpin dan negarawan Kalokagathos yang elok dan baik sehingga dapat hidup tertib dan teratur dalam relasi individu, sosial dan lingkungan alam sekitarnya. Untuk itu menjadi perhatian pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal agar tetap konsisten mempertahankan marwah pendidikan pemimpin dan negarawan.
Kita perlu menyadari bahwa saat ini sangat sulit ditemukan pemimpin dan negarawan yang berorentasi pada kebaikan sebagaimana dicirikan manusia paripurna Kalokagathos. Banyak tokoh yang dihadirkan namun mereka masih sebatas pada level aristokrat dan oligarki belum melampaui keduanya. Masih berorientasi pada kepentingan pragmatis jangka pendek, rakus kekuasaan untuk mengambil keuntungan bagi dirinya dan keluarganya, belum selesai dengan kepentingan perut dan sekitarnya. Bahkan seringkali menjadi beban bagi negara dari generasi ke generasi. Dan kita tidak harus menunggu satu abad, satu dekade atau satu generasi yubileum, untuk lahirnya pemimpin tersebut. Namun kita bisa membentuk pemimpin dan negarawan yang elok dan baik sesuai kebutuhan kita. IPDN yang telah lama mengadopsi dan mengembangkan pendidikan (paideia) kader ala Platon di Lembah Manglayang sepatutnya dikawal untuk terus melahirkan pemimpin dan negarawan Kalokagathos dengan sistem yang tepat (tidak menyimpang atas kepentingan pragmatis) guna mengisi kekosongan pemimpin dan negarawan yang ideal. Semua proses dari awal sampai pada output harus tetap dalam kerangka ideal agar selaras dengan hakikat awal lembaga ini di dirikan. Ini berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pendidikan dari hulu sampai pada hilir. *Semoga* (Pembelajar filsafat kelas extension) Terinspirasi dari Dialektika filsafat pendidikan politik Platon karya Wibowo & Cahyadi






